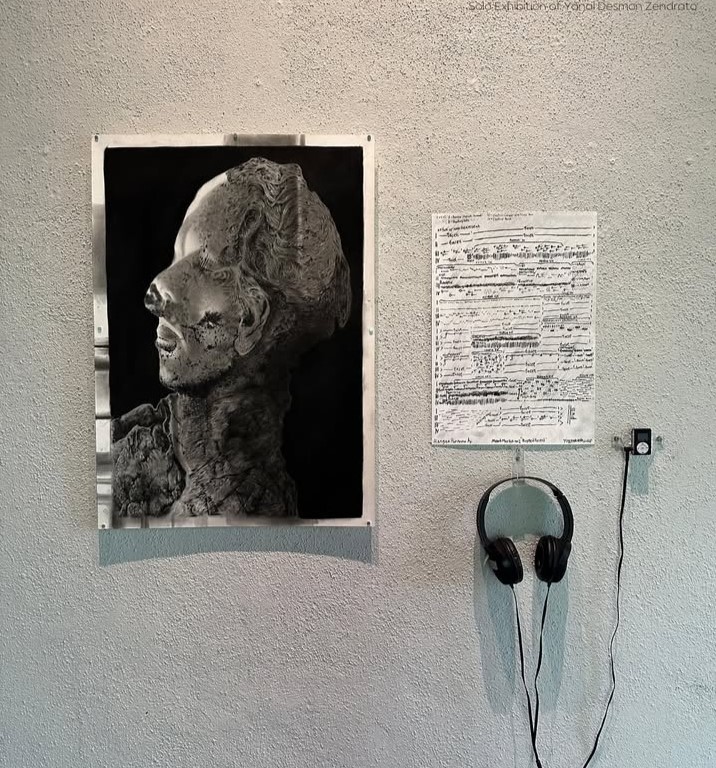Menikmati Setiap Kejutan di Buku Mendengar di Bali
13-12-2017 02:56
Art Music Today

Oleh: Nurul Hanafi
Pertemuan antara Gigih dengan musik Bali—seperti tertuang di buku ini—mirip pertemuan antara Takemitsu dengan musik Jepang tradisional. Takemitsu besar dengan referensi musik Barat yang didengarnya dari tentara Amerika dan cenderung enggan atau malah agak benci dengan musik Jepang sendiri. Baru setelah dekade 1960an Takemitsu tertarik musik tradisional, lalu dibuatlah konserto untuk shakuhachi, biwa, dan orchestra: November Step.
Dalam banyak sisi, buku “Mendengar di Bali” yang diterbitkan oleh Art Music Today terasa menarik, terutama karena didukung alur yang runtut, enak dibaca, impresif, berbobot, sekaligus ringan, sehingga pembaca awam pun bahkan akan menikmatinya tanpa banyak berkerut kening.
Seperti uraian Erie Setiawan dalam catatan pengantar, bahwa Gigih memang tidak semata-mata hadir di Bali secara pasif. Gigih berusaha sedemikian rupa agar apa yang ia alami juga bisa kita rasakan, kita hayati, dan kita tangkap maknanya.
Selama sebulan penuh (31 hari) Gigih bukannya mengurung diri di kamar melainkan membuka diri, menajamkan indera, dan membiarkan berbagai hal yang ada di sekitarnya masuk dalam kesadaran secara utuh dan dalam taraf tertentu mengusik cara pandangnya dan bahkan mempengaruhi. Gigih tidak membawa beban apapun di pundak dan pikirannya. Bebas lepas dan menikmati setiap kejutan yang hadir dengan senang hati. Karena itu, wajar jika catatan-catatan yang ia tuliskan terasa segar dan hangat, baik yang membahas perjalanan wisata sejarah, budaya, maupun yang secara khusus membahas musik.
Ia punya bekal musik dan khasanah budaya dalam dirinya, yang berbeda corak dan karakteristik dengan apa yang ia temui di Bali, namun segala corak dan karakteristik yang baru saja diakrabinya itu tidak mendorongnya untuk membanding-bandingkan mana di antara kedua kebudayaan itu (Jawa dan Bali) yang lebih kuat atau orisinal.
Terlepas dari banyak sisi menarik di buku setebal 178 ini, Gigih masih sering tampak canggung menampilkan refleksi individu secara lebih mendalam, padahal itu potensial, dan lebih cenderung menyampaikan pengalaman demi pengalaman secara apa adanya.
Seperti misalnya saat Gigih membicarakan berbagai versi rekaman Konserto Piano No.3 karya Beethoven, dan merenungi soal interpretasi dalam musik. Sayangnya ia tidak mengungkapkan pendapat pribadinya secara lebih detail, umpamanya bagaimana pengalamannya menyimak berbagai interpretasi atas karya-karya yang ia kagumi. Tentu akan menarik sekali apabila saya bisa mendengar pendapat pribadi Gigih, juga untuk pembaca lainnya.
Saya sendiri suka memperhatikan berbagai tafsir La Mer karya Debussy. Pengalaman membandingkan berbagai tafsir akan mempertemukan pendengar terhadap tafsir yang paling ia favoritkan. Kemudian apakah setelah menemukan tafsir favorit ini seorang pendengar akan merasa cukup dan tidak tertarik lagi dengan tafsir sesudahnya? Ini kan subjektif, masing-masing orang punya pengalaman berbeda.
Kalau melihat berbagai pilihan tafsir atas satu komposisi, saya akan pilih tafsir yang paling panjang lebih dulu. Resiko kecewa lebih minim. Celakanya kalau misalnya kita dengar: “Eh... Psalm 130 karya Lily Boulanger asik sekali, lho. Menurut saya itu karya terbaiknya,” lalu tanpa tanya lebih lanjut siapa yang memainkannya, kita langsung cari karya itu, misalnya di YouTube, dan kecewa lalu bilang: "ah, enggak. Menurut saya itu karya biasa saja".
Dalam kondisi seperti ini, karya bagus bisa tercoreng gara-gara performernya. Untuk kasus karya kontemporer, yang belum mapan dalam kanon musik, risikonya lebih mengkhawatirkan lagi. Ini kan masalah yang bisa digali Gigih lebih jauh.
Catatan dengan judul Tacet (Hari ke-7) dan Rekaman Lagu Mbak Sandrayati Fay (Hari ke-8) tidak menarik minat saya secara pribadi. Bukan berarti itu catatan itu buruk, tapi ketertarikan saya bisa bangkit kalau saya menemukan sesuatu yang melebihi urusan “jadwal kesibukan”, sementara sesuatu itu tidak saya temukan di sana. Oke. Unsur guyub rukun bermusik dengan banyak kalangan bisa disebut memang. Tapi nampaknya saya terlalu berharap Gigih bersedia bicara filosofis tentang keguyub-rukunan itu. Misalnya, toh ia seharusnya bisa bilang bagaimana seandainya pemain kontrabas tidak jadi hadir, efeknya kira-kira bagaimana. Artinya pembaca akan sangat diperkaya jika mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekedar catatan peristiwa. Bisa dikembangkan menjadi esai panjang. Ia cukup menambahkan satu paragraf berisi renungan pendek peristiwa kerjasama musikal yang tertuang di situ. Itu sudah jadi nilai plus. Sederhana saja. Misalnya: setelah rekaman selesai, saya membayangkan seperti apa kesannya jika kami bermain dalam ruangan yang gelap gulita.
Beberapa catatan lain yang menurut saya menarik adalah: Internet dan Karya-karya Musik Baru #2 (Hari ke-11). Daftar referensi judul judul karya gamelan baru memperkaya wawasan pembaca; Tentang Siklus Bosan (Hari ke-13) juga bagus. Renungan tentang kekuatan konsentrasi dan nilai pentingnya; Takemitsu, Identitas, dan Musik Antar Bangsa (Hari ke-14) apik juga. Uraian panjang yang sangat informatif tentang Takemitsu. Bagian itu bagus. Tapi catatan selanjutnya, Melihat Latihan Gamelan di Sanggar Ceraken, saya berharap bahwa di tengah ramai suara gamelan Gigih terkenang dengan musik Takemitsu yang biasa didengarnya dan merasakan efek tertentu. Mungkin sebenarnya ia merasakan itu, tapi tidak dituliskan. Bagaimana pun, uraian tentang efek ini akan memberi kebulatan ide bagi sebuah tulisan.
Mendengar Kembali Takemitsu (Hari ke-15) oke juga. Tapi saya tak tahu apakah Gigih menganggap All in Twilight adalah karya puncak Takemitsu ataukah sekadar sangat berselera dengan itu. Bagiku, sukar ditentukan karya puncak Takemitsu. Banyak karya menduduki posisi puncak sekaligus. Suatu saat Gigih agaknya perlu menjelaskan tentang pilihannya atas All In Twilight. Memang kalau dibandingkan komposisi gitar Takemitsu lainnya itu paling hebat. Tapi kalau terhebat secara keseluruhan karya… saya tak menyimpulkan sejauh itu. Bagiku, pandangan Gigih tentang All in Twilight terlalu general. “Setiap mendengarkan karya ini, saya merasa terbawa pada sebuah dimensi seperti mimpi” (Hal 84). Semua karya terbaik Takemitsu bagiku punya ciri seperti itu.
Pada catatan Membuat komposisi untuk Sape, Flute, Cello dan Piano (Hari ke-16) Gigih begitu terinspirasi dengan Takemitsu, sampai-sampai menggunakan judul yang pernah dipakai pula oleh Takemitsu, Between Tides.
Beberapa tulisan menarik lainnya tentang pengalaman visual dan auditif misalnya tentang Monumen Bajra Sandhi (Hari ke-20) dan Drama Tari Arja (Hari ke-21). Sebenarnya bisa lebih manis lagi seandainya Gigih bersedia menambahkan satu paragraf saja yang isinya adalah abstraksi pengalaman. Misalnya di akhir hlm 105 ditambahkan: emosi lebih kuat daya sentuhnya ketimbang ide filosofis yang meskipun banyak mengandung kebenaran namun diuraikan dengan bahasa rumit, dan seterusnya… Abstraksi itu tidak harus sepenuhnya benar, tapi fungsinya adalah merangsang pembaca untuk berpikir lebih lanjut. Mereka mungkin mendebat. Adanya perdebatan itu justru menarik. Banyak tulisan Gigih yang punya peluang seperti itu. Artinya, bahan yang sudah disusun sejak paragraf awal memungkinkan ia ke arah itu
Ending tulisan Goa Gajah, Candi Gunung Kawi, Nekara Bulan Pejeng adalah ending tulisan yang paling menarik dalam buku ini: “Merasakan keheningan bersembahyang adalah bunyi yang indah di dalam sanubari. Jikalau kita bisa menghargai kesunyian, kita akan bisa menghargai suara, menghargai semesta.”
Sebagai komponis dan pengajar di ISI Yogyakarta Gigih punya rencana-rencana jangka panjang dan berbagai impian, namun, di hadapan segala unsur kehidupan di Bali yang menyentuh syaraf-syaraf indera dan pikirannya, Gigih justru menjadi rendah hati dengan segala rencana dan impian itu.
Data Buku:
Judul: Mendengar di Bali – Sebuah Buku Harian Bunyi
Penulis: Gardika Gigih Pradipta
Cetakan: I, 2017
Ukuran: 14 x 21 cm
Tebal: 178 halaman (Hard Cover)
Penerbit: Art Music Today
Harga: Rp. 120.000,-
Buku ini adalah catatan harian komponis-pianis Gardika Gigih selama 31 hari tinggal di Bali (Juli – Agustus 2017). Setiap hari tanpa henti ia mencatatkan pengalaman kreatifnya, mulai dari mengunjungi sanggar, menonton pertunjukan gamelan, aktifitas rekaman musik, hingga impresi-impresi atas karya musik yang ia dengar dengan dilengkapi data historis yang informatif. Buku ini adalah buku Gardika Gigih yang kedua, setelah Merindukan Awajishima (2016), yang menceritakan proses kreatif bermusik selama di Jepang.
Pembelian: 0895341875712 (WA)
Login Member

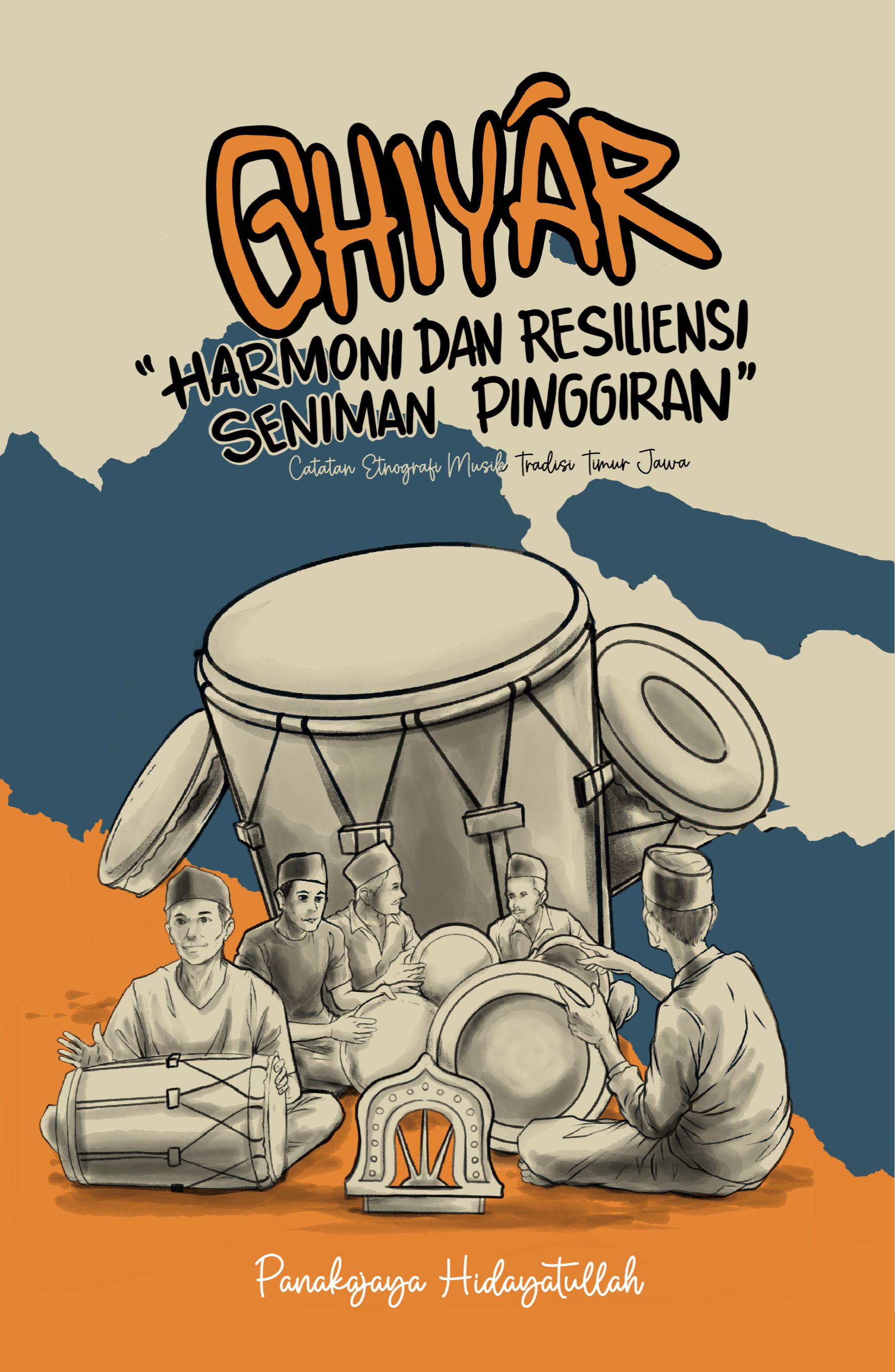


239 x dilihat

1210 x dilihat

1308 x dilihat


1449 x dilihat

906 x dilihat

1714 x dilihat

1266 x dilihat

1869 x dilihat

1655 x dilihat

1795 x dilihat

3156 x dilihat

1838 x dilihat

8198 x dilihat

2591 x dilihat

3678 x dilihat

1970 x dilihat

2639 x dilihat

3054 x dilihat

2044 x dilihat

1751 x dilihat

4998 x dilihat

7306 x dilihat
3873 x dilihat

2416 x dilihat
1973 x dilihat
2030 x dilihat

2321 x dilihat
1866 x dilihat
2582 x dilihat

2209 x dilihat

1946 x dilihat

11700 x dilihat

5678 x dilihat